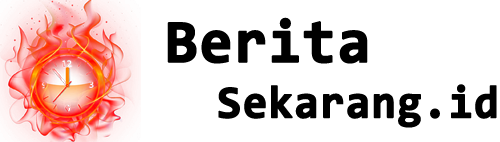Polemik Kuliner Bandung: Penjual Mie Babi Berpeci dan Berhijab, Satpol PP Turun Tangan Atasi Keresahan Publik
BANDUNG, beritasekarang.id – Kota Bandung, yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dengan toleransi yang tinggi, baru-baru ini dikejutkan oleh sebuah fenomena viral yang memicu perdebatan sengit di media sosial. Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan aktivitas di salah satu gerai makanan yang secara eksplisit menjual olahan babi (mie babi). Namun, yang menjadi sorotan publik bukanlah menu non-halal yang dijual—mengingat keberagaman kuliner adalah hal lumrah—melainkan penampilan para pramusajinya yang mengenakan atribut identitas Muslim yang kental, yakni peci dan hijab.
Kontradiksi visual antara produk yang dijual (haram bagi Muslim) dengan simbol pakaian yang dikenakan (identik dengan Muslim) ini sontak memicu keresahan. Publik menilai adanya potensi ambiguitas yang dapat menyesatkan konsumen (misleading), terutama bagi wisatawan atau warga yang mungkin kurang teliti. Merespons kegaduhan ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan.
Antara Hak Usaha dan Etika Simbolik
Kasus ini membuka ruang diskusi yang menarik mengenai batasan etika dalam bisnis kuliner di Indonesia. Secara hukum, menjual makanan non-halal adalah praktik yang legal dan dilindungi, selama mematuhi regulasi pencantuman keterangan “Non-Halal” yang jelas. Namun, persoalan menjadi rumit ketika masuk ke ranah simbolik.
Di Indonesia, peci dan jilbab bukan sekadar tren mode; keduanya adalah penanda identitas keagamaan yang kuat. Bagi mayoritas konsumen Muslim, melihat penjual mengenakan atribut tersebut secara tidak sadar membangun persepsi “aman” atau “halal”. Ketika atribut ini digunakan dalam ekosistem penjualan produk babi, terjadi disonansi kognitif yang memicu rasa tertipu pada publik.
Tindakan Satpol PP yang mendatangi pedagang tersebut dinilai sebagai langkah preventif yang tepat. Fokus aparat bukanlah melarang jualan babinya, melainkan memastikan tidak adanya unsur manipulasi psikologis terhadap konsumen. Dalam sidak tersebut, aparat menekankan pentingnya transparansi. Jika warung menjual babi, maka atmosfer dan identitas visualnya harus jujur, agar tidak ada konsumen Muslim yang “terjebak” masuk karena melihat pramusajinya berhijab.
Perspektif Perlindungan Konsumen
Isu ini juga relevan jika ditarik ke dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Penggunaan atribut yang identik dengan standar halal pada produk non-halal dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi yang kabur.
Kejadian di Bandung ini menjadi pelajaran mahal bagi para pelaku usaha kuliner. Sensitivitas budaya dan agama (cultural sensitivity) adalah aset tak berwujud yang krusial. Pemilik usaha, meskipun mungkin bukan berasal dari kalangan Muslim, seharusnya memahami sosiologi masyarakat setempat. Mempekerjakan karyawan berhijab untuk mengolah atau menyajikan babi, meskipun mungkin karyawannya bersedia, tetap akan menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang memegang teguh nilai halal-haram.
Pentingnya Edukasi dan Keterbukaan
Klarifikasi dari pihak pengelola dan pembinaan dari pemerintah daerah diharapkan dapat meredakan ketegangan. Kasus ini tidak boleh digiring ke arah sentimen SARA yang destruktif, melainkan harus didudukkan pada proporsi etika bisnis.
Ke depan, standardisasi visual untuk gerai non-halal mungkin perlu dipertegas, tidak hanya sebatas tulisan kecil di menu, tetapi juga mencakup aspek penampilan pelayanan. Bagi konsumen, kejadian ini adalah pengingat untuk selalu kritis dan teliti (tabayyun) sebelum membeli, tanpa hanya mengandalkan asumsi visual semata. Bandung harus tetap menjadi kota kuliner yang ramah bagi semua, di mana transparansi menjadi jembatan kenyamanan bagi penikmat makanan halal maupun non-halal.