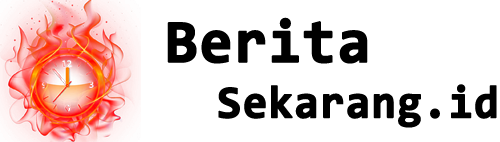Saya Memutuskan Pindah dari Jogja Setelah Belasan Tahun Tinggal: Kota yang Tak Lagi Sama
Keputusan untuk pindah dari Jogja setelah belasan tahun tinggal bukanlah keputusan yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang: bertahun-tahun menimbang, menyangkal, lalu akhirnya menerima bahwa tidak semua tempat yang pernah kita cintai bisa terus kita tinggali.
Jogja dulu terasa seperti rumah kedua. Kota yang ramah, murah, dan manusiawi. Tapi waktu berjalan, dan kota—seperti manusia—berubah.
Jogja yang Pernah Saya Kenal
Saya datang ke Jogja dengan mimpi sederhana: hidup tenang, cukup, dan dekat dengan kebudayaan. Di kota ini, hidup terasa ringan. Uang tidak harus banyak untuk bisa bahagia. Waktu berjalan lebih lambat. Ruang publik masih bernapas.
Jogja adalah kota yang memberi kesempatan hidup bagi banyak orang dengan modal pas-pasan. Mahasiswa, seniman, pekerja lepas—semuanya punya tempat.
Ketika Kota Mulai Berubah
Perubahan tidak datang dengan ledakan, melainkan pelan dan nyaris tak terasa. Sampai suatu hari, kita sadar bahwa Jogja tidak lagi murah.
- Harga kos melonjak drastis
- Rumah makin sulit dijangkau warga lokal
- Lahan hijau berganti beton
- Kemacetan yang dulu asing kini menjadi kebiasaan
Jogja tumbuh, tapi tidak selalu ramah bagi penghuninya sendiri.
Hidup yang Makin Mahal, Upah yang Tertinggal
Masalah terbesar bukan sekadar mahal, tapi ketimpangan. Biaya hidup naik, sementara penghasilan banyak sektor tetap stagnan. Jogja masih menjual citra “murah”, tapi realitasnya berkata lain.
Kota ini perlahan berubah menjadi:
- Kota wisata
- Kota investasi properti
- Kota singgah, bukan lagi kota tinggal
Bagi mereka yang tidak punya aset atau privilese, bertahan menjadi semakin berat.
Kehilangan Ruang Bernapas
Yang paling terasa bukan angka di rekening, tapi hilangnya ruang hidup. Tempat nongkrong murah tergantikan kafe mahal. Kampung berubah jadi homestay. Sawah jadi perumahan eksklusif.
Jogja terasa semakin padat, semakin cepat, dan semakin kompetitif—hal-hal yang dulu justru membuat orang datang ke sini untuk menghindarinya.
Pindah Bukan Berarti Membenci
Memutuskan pindah bukan berarti membenci Jogja. Justru sebaliknya. Ada cinta yang terlalu besar untuk dipaksa bertahan dalam kondisi yang menyakitkan.
Pergi adalah bentuk kejujuran: bahwa saya butuh kota yang masih memberi ruang untuk hidup, bukan sekadar bertahan.
Jogja tetap punya tempat di ingatan, tapi tidak lagi di rencana hidup.
Fenomena yang Lebih Besar dari Diri Saya
Pengalaman ini bukan kisah tunggal. Banyak orang mengalami hal serupa:
- Warga lama yang tersingkir
- Anak muda yang tak lagi mampu bertahan
- Kota yang tumbuh, tapi tidak inklusif
Ini bukan sekadar cerita personal, tapi cermin krisis perkotaan: ketika kota kehilangan warganya demi citra dan modal.
Menutup Bab, Bukan Menghapus Kenangan
Saya pergi dengan satu kesadaran: kota tidak berutang apa pun pada saya. Tapi saya berutang kejujuran pada diri sendiri.
Jogja akan selalu saya kenang sebagai tempat belajar, jatuh, bangkit, dan tumbuh. Tapi hidup, seperti kota, harus terus bergerak.
Dan kali ini, saya memilih bergerak menjauh.
Related Keywords: pengalaman hidup di Jogja, biaya hidup Jogja mahal, pindah domisili dari kota pelajar, realitas hidup di Yogyakarta, Mojok esai domisili